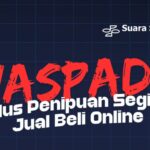Industri radio di Indonesia hari ini sedang berdiri di titik genting. Setelah puluhan tahun menjadi medium paling egaliter—mudah diakses, murah, dan dekat dengan komunitas—radio kini terhimpit oleh dua tekanan sekaligus: derasnya arus platform digital global dan regulasi nasional yang belum sepenuhnya memahami realitas di lapangan.
Revisi UU Penyiaran yang tengah dibahas DPR menjadi momentum penting: apakah regulasi mampu memberi napas baru bagi keberlangsungan radio, atau justru menutup ruang hidupnya secara perlahan.
Masalah pertama yang krusial adalah klausul Analog Switch-Off (ASO) tahun 2028. Di atas kertas, target ini terasa progresif, namun faktanya ekosistem penerima digital (DRM) belum terbentuk. Harga satu unit perangkat receiver masih berkisar ratusan ribu rupiah, jauh dari daya beli mayoritas pendengar. Di sisi lain, investasi transmisi digital menuntut biaya besar: pemancar, encoder, dan perawatan sistem baru. Jika migrasi dipaksakan, ribuan radio lokal mungkin akan runtuh sebelum sempat beradaptasi.
Inggris bisa menjadi contoh dalam masalah ini. Mereka memilih simulcast DAB+ dengan FM selama dua dekade tanpa paksaan ASO, hanya membuka opsi ketika penetrasi perangkat melewati 50 persen rumah tangga. Di Norwegia, ASO diterapkan penuh pada 2017, tapi tetap memberi pengecualian kepada radio lokal agar tetap siaran di FM. Pelajaran dari luar jelas: transisi harus berbasis kesiapan pasar, bukan hanya jadi target administratif.
Masalah kedua menyangkut beban ekonomi migrasi digital. Transisi berarti menanggung siaran analog dan digital secara paralel. Biaya listrik, perawatan, dan infrastruktur menjadi beban ganda. Tanpa insentif, radio menengah dan kecil akan menanggung stranded cost yang mematikan.
Kalau kita mengambil contoh kasus di Jerman, pemerintah federal memberikan subsidi perangkat receiver untuk rumah tangga miskin dan subsidi transmisi untuk radio kecil. Sedangkan Australia mendorong model konsorsium multiplex agar beberapa stasiun radio berbagi infrastruktur digital sehingga biaya lebih ringan.
Masalah ketiga berkaitan dengan kebebasan jurnalistik. Draf RUU masih memuat pasal yang bisa membatasi jurnalisme investigasi, meskipun Dewan Pers sudah menegaskan bahwa itu bertentangan dengan UU Pers 40/1999. Bagi radio berita, investigasi adalah pembeda sekaligus modal kepercayaan publik. Jika dibatasi, radio kehilangan peran watchdog dan hanya tersisa sebagai corong pengulangan.
Filipina dan Afrika Selatan memberi teladan: di sana, regulasi penyiaran tunduk pada konstitusi kebebasan pers, sementara regulator teknis tidak diberi kewenangan membatasi konten investigatif. Dengan cara itu, jurnalisme tetap bisa berfungsi tanpa tertekan oleh lisensi.
Masalah keempat adalah ketidakadilan regulasi dengan OTT audio. Spotify, YouTube Music, hingga platform podcast bebas memonetisasi pasar iklan Indonesia tanpa dibebani regulasi seketat radio siaran. Ketimpangan ini membuat arus iklan bergeser keluar, bukan karena kualitas, melainkan karena perbedaan struktur regulasi.
Permasalahan macam ini sudah dibaca di Eropa. Uni Eropa memiliki Audiovisual Media Services Directive yang dirilis sejak tahun 2018. Konstitusi ini memperluas regulasi penyiaran ke platform OTT: mereka wajib tunduk pada aturan iklan, proteksi konsumen anak, dan kuota konten lokal. Indonesia bisa meniru pendekatan itu agar level playing fieldnya terjaga.
Masalah kelima adalah kurangnya pemanfaatan teknologi digital radio untuk layanan publik. DRM bukan hanya soal kejernihan suara, tetapi juga kemampuan menyalurkan teks lalu lintas, informasi publik, dan peringatan dini bencana.
Jepang dengan sistem J-Alert menjadikan radio digital sebagai kanal utama penyebaran pesan darurat. Amerika Serikat pun menempatkan radio dalam Emergency Alert System (EAS), lengkap dengan kompensasi kontrak layanan publik. Indonesia, negeri yang berada di wilayah “Ring of Fire” dan rawan bencana hidrologi, ironisnya belum menempatkan radio dalam kerangka resmi sistem kebencanaan digital.
Masalah keenam terkait pembatasan bidang usaha melalui NIB/KBLI. Radio hanya diakui pada bidang “penyiaran”. Padahal realitas bisnis memaksa banyak stasiun bertahan dengan proyek periklanan, event, atau jasa komunikasi publik. Tanpa dasar hukum, mereka harus mendirikan PT baru atau “meminjam bendera”. Grup besar mungkin bisa mengatasi ini dengan membuat anak usaha, sementara radio kecil makin terjepit. Korea Selatan memberi contoh dengan memberi izin radio/TV memiliki divisi periklanan & event di bawah badan hukum yang sama. Di Brasil, radio komunitas bahkan diizinkan mengelola proyek iklan lokal & event komunitas agar bisa bertahan.
Dari semua contoh itu, arah bagi Indonesia sebenarnya sudah jelas terlihat. Menurut saya, migrasi digital sebaiknya dilakukan dengan simulcast bertahap, bukan ASO prematur. Pemerintah perlu hadir dengan insentif fiskal dan teknis seperti yang dilakukan Jerman atau Australia. Kebebasan jurnalistik harus dilindungi melalui rujukan eksplisit ke UU Pers, sebagaimana praktik di Filipina dan Afrika Selatan. OTT audio harus diatur dengan prinsip paritas seperti di Uni Eropa. Teknologi DRM sepatutnya dimanfaatkan sebagai infrastruktur publik, sebagaimana di Jepang dan Amerika Serikat. Dan ruang usaha radio perlu diperluas agar tidak hanya terbatas pada “penyiaran”, meniru langkah Korea Selatan dan Brasil yang memberi keleluasaan bagi media untuk bertahan di era digital.
Semua ini bukan sekadar daftar tuntutan industri, melainkan seruan agar negara melihat radio secara lebih adil. Radio bukan “penyintas tua” yang menunggu ajal, tetapi medium yang telah berulang kali membuktikan ketangguhannya: tetap menyala ketika listrik padam, tetap hadir ketika internet macet, tetap menghubungkan warga dengan suara manusia yang dekat dan nyata. Revisi UU Penyiaran bukan hanya soal membagi frekuensi dan memberi izin, tetapi soal menegaskan bahwa suara rakyat—yang murah, sederhana, dan merakyat—masih layak diberi ruang hidup di republik ini.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Radio bukan masa lalu, tapi denyut kepercayaan hari ini.”







 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100