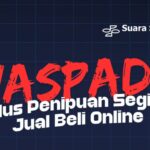Viralnya sosok “Thomas Alva Edi Sound” alias Memed Potensio di media sosial tak lahir dari kehendak algoritma semata. Ia bukan tokoh akademik, bukan musisi, bukan pula tokoh publik dalam arti konvensional. Ia muncul dari video pendek. Seorang operator sound system yang dengan polos dan percaya diri menata mixer sistem suara, meresapinya dalam batin. Dengan lingkar hitam panda di bawah matanya, netizen memberi label integritas, seorang sound engineer yang demi melahirkan masterpiece suara, rela tidak tidur seminggu. Di sekitarnya ratusan orang mengamati setengah terpukau. Di depannya, tumpukan kotak pengeras suara bergetar melahirkan suara berdentum.
Nama “Thomas Alva Edi Sound” menjadi simbol baru. Semacam jimat digital yang dikunyah oleh netizen, ditertawakan, ditiru, kemudian dihidupkan kembali dalam berbagai format parodi, meme, hingga konten kreatif secara global, bahkan oleh tim sepak bola besar seperti Juventus di media sosialnya. Tapi di balik lelucon itu, ada sesuatu yang tidak sedang bercanda: suara.
Bunyi dari speaker besar yang menghentak jalan desa, pinggir kota, perbatasan sawah, atau lapangan kampung itu bukan sekadar suara untuk hura-hura. Ia adalah suara yang ingin didengar oleh sistem yang selama ini terlalu kedap terhadap jeritan kelas bawah. Sound horeg—begitu sebutannya di dunia maya—menjadi fenomena populer yang tumbuh tidak dari dunia hiburan elite, tapi dari dapur masyarakat biasa. Ia tidak hadir di klub-klub berkarpet tebal atau ruang dansa yang dibungkus pagar eksklusif. Ia lahir dari keinginan sekelompok warga yang merasa berhak menikmati pesta, meski tidak punya izin, tidak punya AC, dan tidak punya reputasi untuk masuk ke dunia yang disebut “layak bersenang-senang”.
Dari perspektif psikologi sosial, sound horeg adalah peristiwa kolektif yang sarat makna. Ia mencerminkan kebutuhan manusia untuk menegaskan identitas dalam kelompok. Di sana, ada rasa memiliki, rasa setara, dan rasa bebas. Dalam komunitas yang berkumpul dan menari di bawah sorotan lampu PAR atau moving head dan debu jalanan, mereka tidak sedang mengabaikan norma. Mereka sedang menciptakan norma baru yang terasa lebih jujur bagi hidup mereka. Suara dentuman yang terdengar seperti berlebihan bagi sebagian orang, justru adalah bentuk katarsis bagi yang lain. Mereka telah terlalu lama ditekan oleh tuntutan, stigma, atau sekadar kehidupan yang tak memberi ruang untuk mengekspresikan keberadaan. Bukan lewat diskusi dan unjuk rasa, bass dan treble itu menjadi bentuk tubuh baru dari ekspresi—yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi terasa menggetarkan sampai ke tulang.
Fenomena ini tidak berhenti di ranah hiburan. Ia menyentuh soal ruang publik, soal keadilan atas siapa yang berhak membuat keramaian, dan soal siapa yang punya legitimasi untuk bersuara keras. Kita melihat masyarakat yang selama ini tak mampu membayar tiket dugem, tak tahu rasanya minum di lounge mahal, atau mungkin merasa malu untuk menari di tempat elite. Mereka menciptakan ulang dunia itu dengan caranya sendiri. Tapi bukan tanpa risiko. Pelarangan, teguran moral, hingga fatwa keagamaan menghujani mereka. Lalu, dengan cerdas, istilah baru pun lahir: sound festival mengganti istilah sound horeg yang disemati label haram. Sebuah cara melawan bukan dengan keras, tapi dengan kosa kata.
Di titik ini, kita bisa membaca sound horeg sebagai petanda zaman. Ini bukan sekadar tentang bunyi. Ini tentang bagaimana masyarakat bawah menolak dimatikan oleh sistem yang terlalu lama hanya mengatur tanpa mendengar. Ini tentang tubuh-tubuh yang menari bukan karena sedang berpesta, tapi karena sedang membebaskan diri. Ini tentang keberanian untuk berkata, “Kami juga punya malam, kami juga ingin bahagia.”
Bagi kita yang hanya menjadi penonton fenomena ini di layar ponsel, barangkali perlu sejenak berhenti tertawa. Sebab mereka yang kita ledek sebagai “kampungan” atau “gangguan sosial”, sedang menjalani bentuk keberadaan yang tidak diberikan oleh kota atau negara. Mereka tidak sedang mencoba masuk ke dunia kita. Mereka sedang menciptakan dunianya sendiri, yang bisa jadi lebih jujur daripada ruang-ruang elite yang pura-pura rapi tapi penuh luka diam-diam.
Dan bagi siapa pun yang berada di tengah sound system itu, yang menata kabel, menyusun speaker, menari dalam debu, atau memutar lagu-lagu remix dari YouTube yang dipirsa ribuan orang: semoga kalian tetap sadar bahwa volume itu, bukan sekadar hiburan. Jangan biarkan suara itu memekakkan telinga kalian sendiri dan hati orang lain. Jadikan ia gema kesadaran bahwa setiap getaran punya tanggung jawab. Bahwa dalam hak untuk bersuara, ada juga hak orang lain untuk mendengar dengan damai.
Mungkin ini bukan tentang Thomas Alva Edi Sound. Tapi tentang kita semua—yang sedang belajar, bahwa suara bisa menjadi jembatan, atau bisa menjadi jurang. Tinggal kita pilih mau berdiri di sisi mana.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Menyimak yang bising, menafsir yang tak terdengar.”

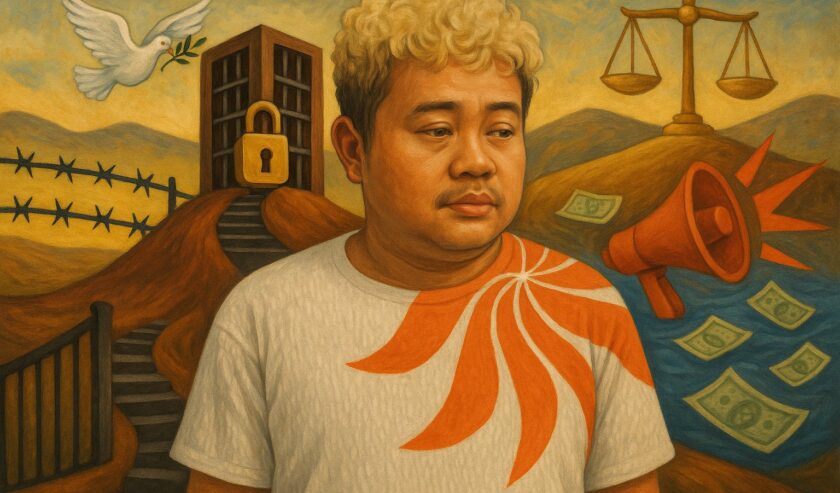





 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100