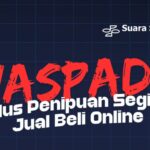Tanggal 17 Agustus 2025, tepat saat Indonesia merayakan ulang tahun ke-80 kemerdekaannya, Bank Indonesia akan meluncurkan sebuah sistem baru dalam lanskap transaksi keuangan nasional: Payment ID. Nama ini mungkin belum akrab di telinga sebagian masyarakat, tapi dampaknya akan menjangkau setiap individu yang menggunakan sistem pembayaran digital, mulai dari pemilik dompet digital, pengguna QRIS, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan omzetnya pada transfer antarbank. Payment ID bukan sekadar kode unik. Ia adalah proyek besar penyatuan identitas keuangan warga negara dalam satu sistem terpusat, berbasis pada NIK, dan digadang-gadang akan menjadi fondasi baru untuk efisiensi, keamanan, dan inklusi finansial nasional.
Bank Indonesia menjelaskan, sistem ini dirancang sebagai respons terhadap tantangan zaman: transaksi yang makin tersebar di banyak platform, sulitnya deteksi penipuan dan pencucian uang, serta kebutuhan pemerintah akan data real-time yang presisi dalam menyalurkan bantuan sosial, mengevaluasi konsumsi, hingga menyusun kebijakan fiskal berbasis perilaku transaksi. Payment ID dijanjikan sebagai jembatan menuju sistem pembayaran yang lebih transparan, akurat, dan saling terhubung, di mana jejak digital finansial seseorang, mulai dari pengeluaran e-wallet hingga tagihan kredit bank, bisa dikenali dan dianalisis dari satu identitas tunggal.
Pemerintah menjanjikan keamanan data sebagai prioritas utama. Data yang ditautkan dalam Payment ID—NIK, rekening bank, dompet digital, hingga pola belanja—disebut akan dienkripsi, dilindungi oleh sistem otorisasi berbasis izin (consent), dan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tidak ada lembaga, kata BI, yang boleh mengakses data kita tanpa seizin kita. Bahkan setiap transaksi yang melibatkan Payment ID nantinya diklaim akan tetap memberikan kontrol kepada pemilik data. Pemerintah juga menyatakan bahwa sistem ini tidak akan mengganggu cara masyarakat bertransaksi. QRIS tetap bisa dipakai seperti biasa, e-wallet tetap aktif, hanya saja kini semuanya berada dalam satu peta data yang utuh dan tak terputus.
Terdengar menjanjikan. Bahkan bisa dibilang revolusioner. Namun sebagaimana setiap revolusi digital, yang perlu kita tanyakan bukan hanya apa yang akan ia ubah, tapi juga siapa yang bisa terdampak, siapa yang berkuasa atas datanya, dan siapa yang mungkin tercecer di pinggir jalan transformasi.
Karena sesungguhnya, dalam banyak catatan dunia, integrasi sistem identitas finansial yang terlalu cepat dan terlalu terpusat, bisa menjadi lubang gelap bagi hak-hak sipil warga negara.
Saya berusaha menggali informasi di berbagai negara belahan dunia ini yang menggunakan sistem serupa. Lewat bantuan mesin peramban digital dan sistematisasi dari akal imitasi (AI) didapatkan sejumlah data yang bisa menjadi cermin kita. Data itu terhimpun dari situs-situs berita kredibel, laporan evaluasi lembaga resmi, dan ulasan profesional yang bisa dipertanggungjawabkan.
Salah satunya India. Negara ini mencobanya lewat Aadhaar, sistem identitas biometrik yang mirip konsepnya dengan Payment ID. Miliaran data warga dikumpulkan, dihubungkan dengan rekening bank dan akses bantuan sosial. Tapi celahnya segera terbuka: ribuan orang kehilangan akses pada jatah pangan hanya karena gagal verifikasi biometrik. Lansia yang sidik jarinya aus, buruh kasar dengan tangan kapalan, atau warga miskin tanpa koneksi internet menjadi korban dari sistem yang tidak menyisakan ruang untuk ketidaksempurnaan manusia. Tak sedikit laporan menyebutkan, kelaparan yang berujung kematian terjadi karena sistem terlalu percaya pada akurasi data dan lupa bahwa hak hidup tak boleh tergantung pada kekuatan sinyal.
Tiongkok memiliki kisah yang lebih kelam: Social Credit System, sistem integrasi data yang menilai “kelayakan” warganya berdasarkan perilaku finansial dan sosial. Skor rendah bisa membuat seseorang tak bisa naik pesawat, tak bisa menyekolahkan anak, atau bahkan tak bisa membuka rekening baru. Dengan alasan efisiensi dan keamanan, negara mengubah data menjadi alat kontrol. Ironisnya, pelanggaran kecil seperti membayar tagihan terlambat bisa berbuntut pada hukuman sosial. Tak ada transparansi dalam mekanisme banding, tak ada peringatan yang cukup sebelum sanksi dijatuhkan. Seolah sistem berkata: “Data Anda mencerminkan siapa Anda, dan kami tak perlu bertanya lebih jauh.”
Di Kenya, sistem identitas digital Huduma Namba menuai gugatan karena justru menyisihkan kelompok minoritas yang sejak awal kesulitan mendapat pengakuan administratif. Bukannya mengurangi diskriminasi, sistem itu justru mengabadikan ketimpangan dalam bentuk digital: siapa yang tak punya data, tak punya akses. Di Nigeria, sistem NIN (National Identity Number) dipakai untuk memblokir akses ke jaringan telekomunikasi bagi jutaan orang yang belum registrasi. Komunikasi digital, transaksi keuangan, hingga koneksi sosial, lenyap begitu saja dalam sehari. Semua atas nama penertiban. Semua dalam nama sistem.
Kita tentu berharap Indonesia tidak mengulang cerita itu. Tapi harapan tak boleh membuat kita buta. Maka “Catatan Pemred” ini bukan untuk menggagalkan kebijakan, bukan pula untuk menebar kecemasan. Ini adalah ajakan untuk menyadari: bahwa di balik digit-digit ID yang tampak rapi, ada konsekuensi besar terhadap bagaimana negara mengenali warganya. Bahwa dalam sistem sebesar Payment ID, kita harus memastikan bahwa tidak ada warga yang terhapus karena ketidaksesuaian data, tidak ada petani tua yang ditolak bantuan karena tak punya akses digital, tidak ada anak muda yang dikejar sistem hanya karena membeli sesuatu yang sistem nilai sebagai tidak wajar.
Di lain sisi, ada juga satu celah krusial yang kerap terlewat dalam euforia teknologi: keamanan data dan kesiapan hukum yang mengikatnya. Janji enkripsi, otorisasi berbasis persetujuan, hingga kepatuhan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdengar menenangkan, tapi sejarah dan pengalaman menunjukkan bahwa janji teknologi tanpa fondasi kelembagaan yang kuat kerap berujung pada kerapuhan yang berbahaya.
Kita telah melihat bagaimana India, lewat sistem Aadhaar, justru membuka celah penyalahgunaan saat miliaran data biometrik warga bocor diperjualbelikan secara ilegal. Nigeria memblokir jutaan nomor ponsel demi disiplin keamanan identitas, sebelum rakyatnya punya jaminan privasi yang jelas.
Bahkan di tanah kita sendiri, kebocoran data BPJS Kesehatan, akun e-commerce, dan aplikasi keuangan pernah terjadi tanpa pemulihan memadai. Ini bukan soal kapasitas teknis semata, tapi soal willpower etis dan keberanian regulatif, apakah otoritas kita benar-benar siap menjaga integritas data warga dengan kehati-hatian maksimal?
Sebab Payment ID bukan sekadar sistem pengenal, ia adalah pintu masuk menuju arsitektur kontrol berbasis data. Jika dijalankan tanpa pengawasan independen yang kuat dan transparansi institusional yang akuntabel, ia berpotensi mengubah identitas menjadi instrumen kekuasaan, bukan perlindungan.
Maka sebelum kita menyerahkan seluruh rekam jejak transaksi kepada satu sistem terpusat, kita perlu bertanya: apakah sistem ini benar-benar dibangun untuk melayani, atau diam-diam menyusun ulang cara negara mengenali dan mengatur warganya? Lalu soal keamanan data, dalam konteks ini, bukan sekadar protokol, tapi tanggung jawab moral dan politik yang menyentuh hak paling dasar: menjadi manusia yang tetap utuh di hadapan negara digital.
Kita perlu bertanya, bukan karena kita menolak teknologi, tapi karena kita mencintai hak-hak kita sebagai warga. Kita berhak tahu siapa yang menyimpan data kita, siapa yang mengaksesnya, dan untuk tujuan apa. Kita berhak tahu apakah data itu bisa dipakai untuk mengawasi kita secara diam-diam. Kita berhak menolak jika sistem itu digunakan bukan untuk pelayanan, melainkan untuk pembatasan.
Kita tidak boleh menjadi warga digital yang diam.
Payment ID adalah simbol kemajuan, tapi ia juga bisa menjadi alat kekuasaan. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa ia tetap berada dalam kendali publik, bukan hanya dikendalikan oleh sistem. Refleksi ini penting bukan untuk membatalkan langkah, tetapi untuk mengawalnya dengan kesadaran. Karena setiap warga negara berhak menjadi bagian dari sistem, tanpa kehilangan hak untuk bersuara tentang sistem itu sendiri.
Selamat menyambut bulan kemerdekaan. Semoga kemerdekaan digital kita tidak berhenti di gawai, tapi juga hidup dalam kesadaran hak dan kewaspadaan sipil.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Di balik algoritma dan identifikasi, hak sipil tetap tak boleh disimplifikasi.”




 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100