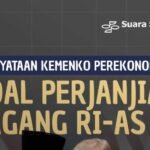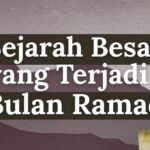Di banyak panggung politik, jatuhnya seorang pemimpin seringkali diawali bukan oleh besarnya kesalahan teknis kebijakan, melainkan oleh kecilnya jarak empati yang ia bangun dengan rakyatnya.
Pati, di Agustus yang panas ini, menjadi laboratorium sosial yang memperlihatkan bagaimana kata-kata bisa menjadi api yang menjalar lebih cepat dari keputusan tertulis.
Satu diksi, satu gestur tangan yang meremehkan, satu nada suara yang mengeras seperti baja, dapat memadatkan kekecewaan yang berserak menjadi gelombang massa.
Dalam sosiolinguistik, gestur dan intonasi bukanlah pelengkap, melainkan inti dari makna yang dibaca publik; ia adalah paralinguistic cues yang menjadi bagian dari “pesan” itu sendiri.
Di ruang publik yang semakin terlatih membaca tanda, diksi bukan hanya menyampaikan kebijakan, tetapi memanifestasikan relasi kuasa.
Peristiwa ini mengingatkan pada pola serupa di beberapa “people power” lain yang sepadan konteksnya, dari Filipina era Estrada hingga gelombang massa di Thailand 2006.
Kesamaan yang kentara adalah hilangnya persepsi kejujuran dan otentisitas dalam komunikasi politik.
Di Filipina, bahasa tubuh yang angkuh dan narasi penuh pembelaan diri Estrada tak mampu menutupi korupsi yang terendus.
Di Thailand, Thaksin jatuh bukan hanya karena kebijakan yang dipersoalkan, tapi juga karena cara ia memoles citra hingga rakyat mencium aroma kepalsuan.
Dalam semantik politik, makna bukan hanya ditentukan oleh leksikon yang dipilih, tetapi oleh konotasi yang dibentuk dari sejarah tutur sebelumnya.
Publik punya memori; mereka membaca hubungan antara apa yang diucapkan hari ini dengan jejak tutur kemarin.
Maka ketika Bupati Pati mengucap “50 ribu pun saya tidak gentar”, maknanya tak lagi sekadar hitungan massa, tetapi sebuah pengumuman simbolik bahwa jarak kuasa telah ditegakkan.
Linguistik memberi kita perangkat untuk membedah ini.
Dari sudut pandang semantik, kata “gentar” dalam pernyataan itu memiliki muatan emosional yang tinggi; ia mengundang oposisi biner antara keberanian pemimpin dan ancaman rakyat, yang secara implisit memposisikan warga sebagai pihak yang menantang negara.
Dalam sosiolinguistik, ini disebut indexicality — ketika pilihan kata mengindeks sikap sosial tertentu.
“Tidak gentar” di sini mengindeks citra diri yang perkasa, tapi sekaligus menandai absennya kerendahan hati yang diharapkan dari seorang kepala daerah di kultur Jawa.
Gestur yang menyertai, tangan yang mengepal, tatapan menunduk ke arah lawan bicara, atau intonasi naik di ujung kalimat. Itu semua memperkuat frame makna itu menjadi pernyataan dominasi.
Rakyat Pati, yang sehari-hari akrab dengan register tutur halus dan basa-basi simbolik, merasakan disonansi: yang hadir di depan mereka bukanlah “bupati” dalam pengertian kultural, melainkan figur kekuasaan yang berjarak.
Komunikasi politik yang otentik selalu menyertakan kerentanan yang terukur: pengakuan bahwa kebijakan bisa salah, bahwa suara rakyat layak menjadi variabel, bahwa pemimpin pun manusia yang perlu belajar.
Di titik inilah manipulasi citra gagal.
Rakyat cenderung cepat membaca kepalsuan — senyum yang hanya muncul di depan kamera, permintaan maaf yang datang setelah tekanan massa, atau jargon partisipasi yang tak diikuti tindakan.
Dalam kasus Pati, momen permintaan maaf justru terbaca sebagai reaktif dan tak konsisten dengan retorika sebelumnya.
Secara semantik, ini menciptakan pragmatic clash antara maksud yang diucap dan makna yang diterima.
Akibatnya, upaya pemulihan citra tidak membangun kembali kepercayaan, melainkan menguatkan kesan bahwa semua adalah strategi menyelamatkan kursi.
Refleksi dari Pati mengajarkan bahwa komunikasi politik bukan sekadar seni merangkai kata atau mengatur panggung visual; ia adalah proses terus-menerus membangun makna bersama, di mana kejujuran dan otentisitas menjadi modal utama.
Pemimpin yang mampu bertahan dalam badai bukanlah mereka yang tak pernah salah, tetapi yang mampu mengubah kesalahan menjadi kesempatan memperkuat simpul emosional dengan rakyatnya.
Di bawah terik matahari alun-alun atau di dingin ruang sidang DPRD, yang diuji bukan hanya kebijakan, tetapi bahasa sebagai cermin jiwa kekuasaan.
Dan ketika bahasa kehilangan kemampuannya untuk memeluk, kekuasaan pun kehilangan alasnya.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Kuasa retak di ujung kata”






 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100