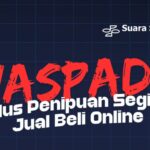Di antara langit mendung akhir Juli yang pelan-pelan merebakkan aroma semangat tujuhbelasan, kita disuguhi adegan simbolik yang sangat Indonesiawi: seorang pemimpin tertinggi memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh yang sebelumnya menempati posisi seberang : Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Bukan semata berita hukum, ini adalah narasi besar. Lebih dari kebijakan, ia adalah drama kultural-psikologis yang membawa kita menelusuri motif-motif batin kekuasaan, warisan gaya kepemimpinan sebelumnya, serta risiko-risiko sistemik yang bisa muncul dari keputusan yang tampak damai namun mengandung konsekuensi laten bagi demokrasi.
Presiden Prabowo, dengan wajah yang kian sering tersenyum dan langkah yang mulai dibingkai sejarah, tampak melanjutkan sesuatu yang telah lebih dulu dirintis oleh pendahulunya, Jokowi. Tapi ia melanjutkannya dengan bahasa yang berbeda, semacam versi baru dari naskah lama. Kalau Jokowi menjinakkan lawan dengan kursi dan kebijakan, maka Prabowo memeluknya dengan amnesti dan pengampunan. Dalam pendekatan Jokowi, lawan-lawan politik dibawa masuk ke panggung birokrasi: diberi jabatan, difungsikan secara administratif, diinkubasi dalam ruang kontrol kekuasaan.
Sementara Prabowo, setidaknya sejauh ini, membingkai proses pelunakan oposisi melalui panggung simbolik: ia bukan hanya mengajak bicara, tapi mengampuni. Memberi pengampunan bukan hanya untuk membebaskan, tapi juga untuk menciptakan citra diri sebagai pemimpin yang tak punya dendam, bahkan terhadap mereka yang pernah berseberangan secara terbuka.
Namun, harus kita akui, dikotomi ini mungkin terlalu prematur. Karena realitas politik Indonesia tidak pernah berhenti bergerak. Setelah kebijakan amnesti dan abolisi ini diumumkan, PDIP — partai asal Hasto Kristiyanto — menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, membuka ruang politik yang lebih luas. Artinya, bisa jadi Prabowo tidak hanya menempatkan lawan di panggung simbolik, tapi juga mungkin akan melanjutkan strategi Jokowi: merangkul lawan dalam panggung birokrasi, membagi kursi, dan membentuk struktur kekuasaan tanpa oposisi nyata.
Di sinilah letak persilangan corak kepemimpinan: Prabowo berpotensi menjahit dua pendekatan ini : teknokratis-pragmatis ala Jokowi; dan heroik-simbolik ala dirinya sendiri. Kita sedang melihat satu arsitektur politik baru, di mana pengampunan menjadi strategi rekonsiliasi sekaligus legitimasi, dan penyerapan oposisi menjadi bagian dari logika kekuasaan total.
Tapi semua ini bukan terjadi tanpa akar. Jika kita ingin menelusuri jejak simbolik dari “politik pelukan” ini, maka kita harus kembali ke satu peristiwa kecil tapi mengandung simbol luar biasa: Asian Games 2018, saat atlet pencak silat Hanifan Yudani Kusumah yang baru saja menyabet emas, mengajak dua tokoh besar politik saat itu, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, dalam satu pelukan merah putih yang monumental. Sebuah panggung spontan di tengah arena yang dipenuhi ribuan sorak-sorai. Dalam pelukan itu, publik Indonesia melihat gambaran utopis tentang persatuan — dua seteru yang selama bertahun-tahun berseberangan, berada dalam satu dekapan, disatukan oleh semangat nasionalisme seorang anak muda.
Simbol ini bertahan lama di imajinasi publik. Pelukan itu menyejukkan di tengah suhu politik yang panas menjelang Pilpres 2019. Tapi lebih dari itu, ia seolah menjadi template bawah sadar, bahwa cara paling efektif untuk mengelola konflik politik di Indonesia bukanlah melalui perdebatan tajam atau pertanggungjawaban terbuka, tetapi melalui momen-momen dramatis yang menyentuh emosi kolektif: pelukan, maaf, dan amnesti.
Kini, Prabowo tampaknya meniru ulang momen itu, tapi dalam skala lebih besar dan formal. Jika dulu ia dan Jokowi hanya dipeluk oleh seorang atlet, kini ia sendiri yang memeluk para bekas rivalnya — secara harfiah maupun simbolik — dan menyebutnya sebagai “rekonsiliasi nasional”. Yang dipeluk bukan hanya orang, tapi juga sejarahnya. Yang diampuni bukan hanya pelaku, tapi juga dosa kolektif elite yang seolah dibereskan dalam satu tanda tangan Keppres.
Namun inilah paradoks yang perlu kita renungkan: apa yang terjadi jika pelukan dijadikan alat untuk menghapus jejak, bukan untuk menyembuhkan? Apa jadinya bila semua yang berseberangan diserap ke dalam, dan sistem hukum yang telah bekerja tiba-tiba dihentikan bukan karena koreksi substantif, tapi karena agenda stabilitas elite?
Ini bukan tentang apakah Hasto atau Tom pantas diampuni. Bukan pula soal legalitas keputusan Presiden, itu hak konstitusional. Tapi ini soal pola sistemik yang membentuk arah demokrasi kita ke depan. Ketika semua jalan konflik diakhiri dengan pelukan elite, maka demokrasi kita kehilangan satu tungku: pembakaran gagasan yang lahir dari pertentangan prinsip.
Dulu kita menolak otoritarianisme karena semua keputusan berasal dari satu suara. Kini kita justru merayakan pemusatan suara dalam balutan kerukunan elite, sambil menyebutnya sebagai stabilitas nasional. Bedanya? Dulu keras, kini lembut. Tapi substansinya? Sama-sama meniadakan suara yang berbeda.
Barangkali kita memang bangsa yang terbiasa menyelesaikan konflik dalam ruang makan, bukan ruang sidang. Tapi apakah kita akan terus memelihara budaya politik yang menyamakan pengampunan dengan penyelesaian, dan pelukan dengan pembersihan? Apakah kita akan membiarkan generasi mendatang tumbuh dalam sistem politik yang tak mengajarkan konsekuensi, tapi hanya memberi pelajaran tentang “siapa kenal siapa” dan “siapa berhutang pada siapa”?
Pelukan Prabowo kepada para mantan lawan bukan sekadar gestur kehangatan. Ia adalah kode. Ia adalah panggung. Dan jika sistem demokrasi kita tak lagi punya oposisi yang independen, maka bukan hanya ruang kritik yang hilang, tapi juga daya tahan negara untuk menegur dirinya sendiri.
Indonesia kini sedang memainkan lakon tentang Raja yang mengampuni semua demi kedamaian istana. Tapi dalam lakon itu, siapa yang menjaga batas antara dendam dan pengampunan? Antara hukum dan belas kasihan? Antara demokrasi dan kooptasi?
Kita butuh waktu untuk merenung, sebelum pelukan-pelukan ini mengubah kita menjadi bangsa tanpa memori kesalahan dan tanpa keberanian untuk bertanya. Karena dalam sejarah, yang paling berbahaya bukanlah pemimpin yang menindas, tapi pemimpin yang menghapus jejak kesalahan dengan senyuman — dan rakyat yang lupa cara mencatat.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Di balik pelukan kekuasaan, perlu ada pilihan tetap menjaga jarak yang kritis.”

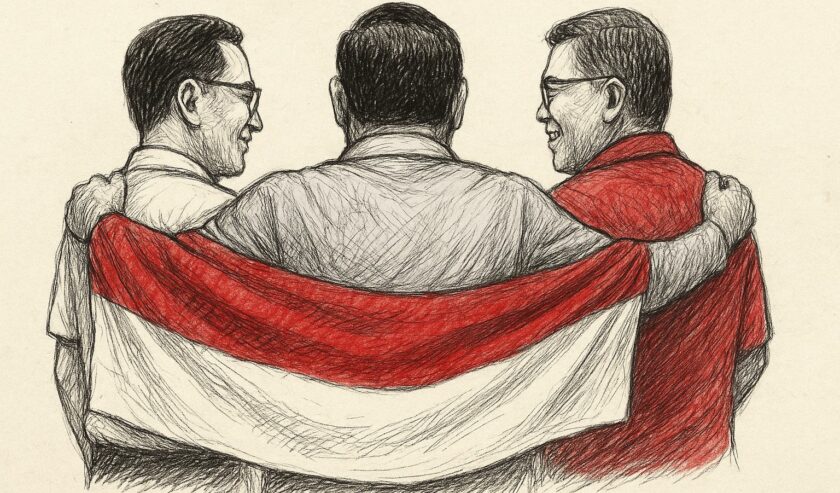



 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100