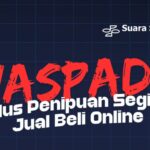Ketika Pemerintah Kota Surabaya mengajukan rencana pinjaman daerah senilai Rp452 miliar untuk menutup defisit APBD-P 2025, kita tidak hanya diminta menilai apakah langkah ini sah atau tidak. Kita sedang diajak melihat ulang: bagaimana sebuah kota membaca realitas fiskalnya dengan jernih, dan memilih keberanian yang tidak gegabah.
Nilai pinjaman Rp452 miliar tersebut, jika ditakar dalam skala nasional, sejatinya berada di tengah. Ia jauh di bawah Semarang yang berani meminjam €150 juta (±Rp2,3 triliun) pada 2023 dari bank pembangunan Jerman untuk sistem BRT. Ia juga lebih kecil dibanding total pinjaman daerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama masa pandemi yang mencapai Rp3,1 triliun. Tetapi ia juga jauh lebih besar dari pinjaman-pinjaman yang pernah dilakukan Kota Malang, Kabupaten Sleman, maupun Provinsi Sulawesi Tenggara.
Data yang saya himpun lewat peramban elektronik dan analisis komparatif dibantu sistem Akal Imitasi (AI) Suara Surabaya Media menunjukkan bahwa Kota Malang pada tahun 2004 hanya meminjam Rp9 miliar untuk merevitalisasi Pasar Comboran. Dengan DSCR mencapai 29,12, proyek itu diselesaikan dalam tiga tahun, dilunasi tepat waktu, dan tidak meninggalkan beban fiskal. Sleman lebih konservatif: dengan DSCR luar biasa tinggi, 122,8 poin, mereka tetap hanya mengambil pinjaman sekitar Rp50 miliar pada 2010-an untuk proyek-proyek layanan publik dan pariwisata. Bahkan Bandung Barat, yang membangun jalan sepanjang 71 kilometer dengan pinjaman Rp285 miliar dari PT SMI pada 2020, mampu mencicil Rp98 miliar per tahun dan melunasinya dalam tiga tahun.
Dalam posisi ini, Surabaya sebetulnya mengambil langkah yang sangat moderat. Nilai pinjaman hanya 3,7–4% dari total pendapatan tahunan. DSCR kota diperkirakan masih di atas ambang minimal (2,5), dan tenor pinjaman dirancang selesai sebelum masa jabatan wali kota usai. Ini berbeda dengan proyek jangka panjang seperti Semarang, yang berani berutang besar karena dukungan pusat dan skema luar negeri. Tapi juga berbeda dari Bandung, yang menolak berutang sama sekali dan mengandalkan efisiensi PAD sebesar Rp170 miliar per tahun, sebuah pendekatan yang dinilai tepat oleh pemimpinnya, tetapi berisiko jika PAD stagnan dan kebutuhan pembangunan mendesak tak bisa ditunda.
Yang mungkin jarang dibahas namun penting untuk dicermati adalah pengalaman Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2006–2010. Dengan skema campuran yang melibatkan APBD, APBN, dan pinjaman daerah, Pemprov membangun RSU Bahteramas—rumah sakit rujukan terbesar di wilayah itu. Nilai pinjamannya tak sebesar proyek Surabaya, sekitar Rp50 miliar. Tapi pelajarannya besar: bahwa pinjaman publik dapat digunakan untuk infrastruktur layanan dasar yang manfaatnya dirasakan rakyat secara langsung. Setelah RSU beroperasi, rujukan pasien ke luar daerah berkurang signifikan dan layanan kesehatan lokal meningkat tajam. Keberhasilan proyek itu bukan karena besar kecilnya pinjaman, tapi karena pinjaman diarahkan tepat, dilaksanakan disiplin, dan dituntaskan sesuai masa jabatan.
Kita tidak bisa mengulang kisah mereka secara persis. Surabaya memiliki kompleksitas yang lain: kebutuhan drainase kota yang menembus Rp1 triliun, kemacetan kronis di jalur Wiyung–Jambangan, dan kebutuhan penerangan jalan di ribuan titik permukiman. Tapi justru karena kebutuhan itu tidak lagi bisa ditunda, maka keputusan untuk mengambil pinjaman harus dibaca dalam kerangka “kesanggupan menyelesaikan yang tertunda,” bukan sebagai “upaya menyembunyikan yang gagal.”
Peta data pinjaman antardaerah juga memberi kita semacam cermin: tidak semua daerah yang meminjam besar berhasil, dan tidak semua yang menolak utang hidup tanpa risiko. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada jumlah uang yang dipinjam, melainkan pada discipline of execution dan kemampuan untuk menjadikan setiap rupiah sebagai manfaat.
Surabaya memilih untuk tidak tinggal diam. Nilai pinjamannya relatif kecil dibandingkan kapasitas fiskalnya yang diperkirakan bisa menampung hingga Rp6,1 triliun dalam lima tahun. Rasio cicilan tahunan terhadap belanja daerah pun di bawah 1%, jauh dari batas 10% yang lazim digunakan untuk menilai kesehatan fiskal. Tapi tetap saja, ini bukan soal seberapa bisa membayar, melainkan seberapa besar keberanian untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu selesai, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat.
Kemarin telah saya ulas dalam “Catatan Pemred” sejumlah titik kritis dan celah yang harus diantisipasi kota ini jika opsi utang diambil menutup lubang defisit. Hari ini saya gambarkan secara jernih bagaimana peta utang daerah di berbagai wilayah yang relevan dengan kasus Surabaya.
Saya menilai bahwa langkah wali kota kali ini bukan sekadar tindakan fiskal, tapi sebuah pernyataan: bahwa pembangunan kota tak boleh disandera oleh stagnasi pendapatan. Namun tetap saja, legitimasi kebijakan ini tidak boleh ditarik dari perhitungan teknis semata. Legitimasi muncul jika proyek Jalan Wiyung dan JLLB benar-benar mengurai kemacetan, jika banjir dengan diversi Gunungsari surut lebih cepat, jika warga kampung bisa berjalan di lorong terang tanpa rasa takut, dan jika setiap rupiah cicilan dibayar tanpa memotong layanan publik.
Pada akhirnya, utang publik bukan hanya kontrak fiskal. Ia adalah kontrak kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun dari eksekusi, bukan wacana.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Kota besar bukan yang bebas utang, tapi yang jujur menepati kontraknya dengan masa depan.”



 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100