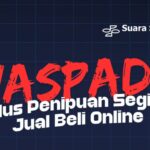Zakat bukan sekadar kewajiban agama, melainkan jembatan sosial yang menghubungkan berbagai kondisi ekonomi masyarakat.
Sebagai salah satu pilar utama Islam, zakat selalu disebut berdampingan dengan salat dalam Al-Quran: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat” (QS. Al-Baqarah: 43).
Jika salat adalah manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan, maka zakat adalah bukti kepedulian terhadap sesama.
Kesalehan tidak cukup hanya diukur dari aspek spiritual, tetapi juga harus tercermin dalam kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah pada Selasa (11/3/2025), sejarah mencatat betapa seriusnya Islam dalam menegakkan kewajiban zakat.
Abu Bakar Ash-Shiddiq bahkan mengerahkan pasukan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Ini menegaskan bahwa keberislaman seseorang tidaklah lengkap tanpa kedermawanan sosial.
Begitu pentingnya zakat hingga para ulama fikih memberikan perhatian besar dalam pembahasan syarat, objek, dan distribusinya.
Namun, di balik aspek hukum yang rigid, terdapat dimensi filosofis yang sering kali terabaikan. Zakat bukan hanya sekadar rutinitas tahunan atau formalitas administratif, tetapi sebuah prinsip keadilan yang tertanam dalam ajaran Islam.
Semua rezeki yang diperoleh manusia, seberapa besar usahanya, sejatinya bersumber dari Allah SWT. Manusia tidak memiliki kepemilikan mutlak atas harta yang dimilikinya.
Kepemilikan sejati tetap berada di tangan Sang Pencipta, sementara manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab.
Islam menetapkan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan.
“Dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19).
Zakat menjadi instrumen keadilan yang memastikan agar kekayaan tidak berputar hanya di antara kelompok tertentu (QS. Al-Hasyr: 7).
Dengan demikian, zakat bukan sekadar pemberian sukarela, tetapi kewajiban yang bertujuan untuk menata kembali distribusi kekayaan.
Dalam konteks modern, zakat memberikan kritik tajam terhadap kapitalisme yang melahirkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.
Sistem ekonomi berbasis keuntungan pribadi semata menyebabkan akumulasi kekayaan pada segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat terjerembab dalam kemiskinan struktural.
Melalui konsep zakat, Islam menawarkan solusi konkret dengan menciptakan keseimbangan sosial.
Sebuah sistem di mana kaum kaya tidak hanya bebas menumpuk kekayaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung.
Zakat juga bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi memiliki dampak psikologis yang mendalam.
Dengan menunaikan zakat, seorang muslim dilatih untuk tidak terikat secara berlebihan pada materi dan membangun kesadaran bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebajikan.
Kata “zakat” sendiri berarti suci, tumbuh, dan berkah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga membersihkan jiwa dari keserakahan dan individualisme yang berlebihan.
Dalam kapitalisme hanya mereka yang bekerja keras yang berhak menikmati hasilnya, maka Islam menegaskan bahwa mereka yang tidak mampu—seperti fakir miskin, difabel, dan korban ketidakadilan struktural—juga memiliki hak atas sebagian harta orang kaya.
Prinsip keadilan distributif ini kemudian diperbaiki oleh Islam menjadi “keadilan distributif-terkoreksi” di mana negara dan individu memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan tidak ada satu pun anggota masyarakat yang terlantar. (nis/saf/ipg)



 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100