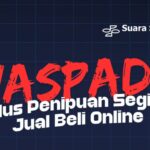Saya membuka catatan dari Pati dalam 2 pekan terakhir ini. Sebuah kabupaten yang berubah menjadi “kelas pembelajaran publik” soal fiskal daerah. “People power Pati” bukan semata amarah, tetapi alarm keras tentang cara pemerintah daerah mengambil keputusan yang menyentuh dapur warga: tarif PBB yang bisa melonjak sampai 250%.
Kementerian Dalam Negeri turun tangan; Akmal Malik Dirjen Otonomi Daerah menegaskan peran provinsi membina dan memfasilitasi kabupaten/kota, sementara Tito Karnavian Mendagri memerintahkan Inspektorat Jenderal mengecek dasar kebijakan. Di sisi lain, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengingatkan gejolak ini lahir dari minimnya partisipasi publik yang bermakna saat merancang kebijakan. Jika warga benar-benar diajak sejak awal, resistensi sebesar itu tak perlu terjadi. Pada akhirnya Bupati Pati membatalkan kenaikan 250% itu, sebuah koreksi yang penting, meskipun terlambat.
Kisah Pati cepat menular: Kota Cirebon menghadapi protes karena rencana kenaikan PBB yang oleh sebagian warga disebut “hampir 1.000%”. Wali kota menyangkal angka ekstrem itu dan berjanji mengkaji ulang, namun secara faktual pemkot mengakui ada kenaikan dan tengah menyiapkan formula baru.
Ini bukan sekadar angka, ini tentang timing, transparansi, dan kredibilitas. “Tidak elok kalau timing untuk menaikkan ini dilaksanakan pada saat sekarang,” kata Ahmad Luthfi Gubernur Jawa Tengah saat menanggapi polemik Pati, sebuah pesan yang menurut saya, pantas dicatat seluruh kepala daerah.
Di Surabaya, narasi berbeda tapi nadanya sama: tekanan fiskal. Di RAPBD Perubahan 2025, pemkot menghadapi defisit pendapatan sekitar Rp700 miliar. Opsi pembiayaan yang dipertimbangkan adalah pinjaman daerah Rp452 miliar untuk proyek infrastruktur strategis.
DPRD mengingatkan efek sampingnya: jangan sampai cicilan pokok dan bunga membuat “program kerakyatan” dikurangi tahun depan. Transparansi skema, beban jangka panjang, dan ruang fiskal untuk layanan dasar, itulah tiga pertanyaan yang harus dijawab di ruang publik, sebelum angka-angka itu diketok.
Jika menengok peta nasional, fragmentasi tekanannya terasa. Kota Palangka Raya, dalam P-APBD 2025, mencatat defisit Rp47,1 miliar dan berharap menutupnya dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Padang menghitung defisit Rp162,2 miliar, menutupnya lewat pembiayaan netto termasuk rencana pinjaman daerah sekitar Rp37,4 miliar.
Kota Cimahi menyebut defisit sekitar Rp60 miliar pada dokumen perubahan KUA-PPAS. Provinsi Riau di awal tahun bahkan bicara risiko defisit miliaran rupiah yang berdampak ke tunda bayar tunjangan pegawai. Pada saat yang sama, Kabupaten/Kota seperti Sanggau juga menyusun P-APBD dengan defisit ratusan miliar yang ditutup lewat pembiayaan. Spektrumnya luas: dari puluhan miliar di kota menengah sampai triliunan di tingkat provinsi.
Di belakang layar, ada konteks nasional yang tidak bisa kita abaikan. Pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi besar sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025. Target penghematan APBN mencapai Rp306,7 triliun, dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp50,6 triliun. Logika akuntansi sederhana: ketika sumber “oksigen” dari pusat dikencangkan, daerah yang struktur PAD-nya rapuh, mengandalkan aliran pusat, akan megap-megap lebih dulu. Di titik ini, literasi fiskal publik, termasuk bagi anggota dewan, OPD, media, dan warga—menjadi penopang utama agar kebijakan korektif bisa dipahami dan diawasi.
Regulasi memberi koridor yang jelas tentang “jalan pulang” menutup defisit. UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dan PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah/ Retribusi Daerah menyediakan ruang intensifikasi-ekstensifikasi pendapatan. Dari penyesuaian tarif sampai optimalisasi basis pajak.
PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pembiayaan, termasuk penggunaan SILPA, penjadwalan ulang program, dan pinjaman daerah yang wajib melalui persetujuan DPRD dan evaluasi pusat. Dan di 2025, Inpres 1/2025 plus pedoman teknis Kemendagri mendorong efisiensi belanja, realokasi ke prioritas, serta penguatan disiplin fiskal. Jalurnya sah, tetapi setiap pilihan mengandung konsekuensi sosial-politik yang hanya bisa diredam dengan desain komunikasi yang matang.
Karena itu, saya memandang strategi daerah menutup defisit tahun ini jatuh pada tiga pakem besar yang sah dan lazim, tetapi harus diramu sesuai karakter PAD dan beban layanan publiknya.
Pertama, efisiensi dan realokasi belanja non-prioritas. Ini langkah cepat yang politisnya lebih “nyaman”, tapi daya ungkitnya terbatas bila struktur belanja sudah sangat rigid.
Kedua, pembiayaan melalui SILPA dan/atau pinjaman daerah. Cara ini ampuh untuk menjaga proyek prioritas, namun membebani ruang fiskal tahun-tahun berikutnya.
Ketiga, intensifikasi pendapatan. Cara ini bisa menggunakan instrumen mulai dari pajak kendaraan, pajak mineral bukan logam dan batuan, BUMD, hingga PBB. Yang terakhir ini paling berisiko sosial jika tak disiapkan data, fase transisi, dan kompensasi yang adil.
Surabaya sedang menimbang opsi kedua, Padang memadukan SILPA dan pinjaman, Palangka Raya mengandalkan SILPA, sementara Pati dan (rencananya) Cirebon memberi pelajaran keras tentang risiko opsi ketiga bila komunikasi dan uji dampak tidak dikerjakan secara serius.
Untuk menulis catatan ini, tim redaksi menjalankan penelusuran digital yang ketat. Meleverage AI sebagai “analyst on call”. Kami mengumpulkan dokumen resmi (UU, PP) dan kebijakan (Inpres 1/2025, panduan efisiensi Kemendagri), menyisir siaran resmi pemda, membuka risalah paripurna/rapat anggaran, serta memberitakan dinamika daerah melalui jaringan media kredibel nasional dan lokal.
Data fiskal kami triangulasikan (misalnya angka defisit dan sumber pembiayaan diperiksa silang antara pemberitaan, pernyataan pejabat, dan kanal resmi), kutipan pakar kami verifikasi asalnya (contoh: analisis KPPOD soal partisipasi publik, peringatan DPRD terhadap dampak pinjaman di Surabaya), dan semua angka yang rawan bias kami pasangkan dengan konteks waktu yang presisi, karena dalam fiskal, satu rapat paripurna bisa mengubah narasi.
Apa pelajaran utamanya?
Pertama, jangan memukul rata. Tidak semua defisit bersifat patologis; banyak yang sekadar “defisit teknis” yang diimbangi pembiayaan sehingga APBD tetap berimbang, seperti Padang dan Palangka Raya.
Kedua, jangan bermain dengan angka target pendapatan yang tidak realistis. Ini bisa menjadi jalan tol menuju revisi yang menyakitkan. Seperti terjadi di Surabaya. “Belum ada intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang ekstrem, ditambah perencanaan target yang terlalu tinggi,” kritik Aning Rahmawati anggota Banggar DPRD Surabaya Surabaya.
Ketiga, jika memilih kartu “pajak daerah”, lakukan uji dampak sosial, phasing, pengecualian yang terarah, bandingkan dengan kemampuan bayar rumah tangga, dan siapkan kanal kompensasi. KPPOD sudah mengingatkan: partisipasi publik yang bermakna itu bukan seremoni sosialisasi, melainkan ko-desain kebijakan…dan itulah pagar pertama menghindari krisis kepercayaan.
Keempat, dan ini krusial untuk 2025: pemerintah pusat sedang mengencangkan ikat pinggang; Transfer Daerah direm, belanja Kementerian/Lembaga dirapikan.
Kepala daerah perlu berpikir “portofolio”: menjaga layanan dasar tetap “on”, mengunci prioritas yang berdampak langsung, dan berani menunda proyek yang “glamour” tapi tak urgent. Di saat yang sama, bangun narasi ke publik. Jangan hanya mengumumkan angka; jelaskan mengapa pilihan A dipilih ketimbang B, siapa yang terdampak, apa mitigasinya, dan kapan evaluasi dilakukan. Bahasa sederhananya: jangan menggedor dompet warga sebelum mengetuk pintu rumah mereka.
Dan akhirnya, kembali ke Pati sebagai cermin. Saya melihat “people power” yang sebenarnya: bukan sekadar massa di jalan, melainkan warga yang menuntut dihormati sebagai pemilik anggaran.
Ketika kepala daerah mengubah arah dan membatalkan kebijakan, itu bukan kekalahan, tapi kesempatan kedua untuk merajut kepercayaan dengan mekanisme yang benar.
Saya berharap para kepala daerah memegang kompas kebijakan seperti memegang gelas berisi air di atas meja kaca: mantap, hati-hati, transparan. Retak kecil di peta fiskal kita hari ini adalah peringatan. Jangan tunggu meja kaca itu pecah.
Jika ada kepala daerah yang membaca catatan ini, izinkan saya menutup dengan simbolisme yang sederhana…
Anggaran itu seperti lampu lalu lintas di simpang padat: hijau memberi laju, kuning memberi jeda, merah memberi batas. Bijaknya, Anda tidak menambah lampu baru untuk memaksa orang berhenti lebih lama; Anda menata arusnya agar semua bisa lewat dengan selamat. Karena pembangunan bukan soal siapa paling cepat tiba, melainkan siapa tiba bersama warganya dalam keadaan utuh.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Keputusan fiskal yang bijak adalah yang tak meninggalkan luka sosial.”

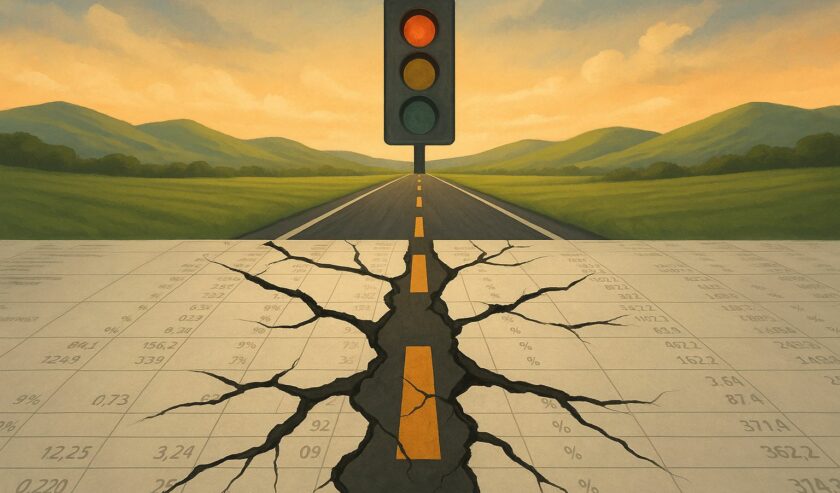





 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100