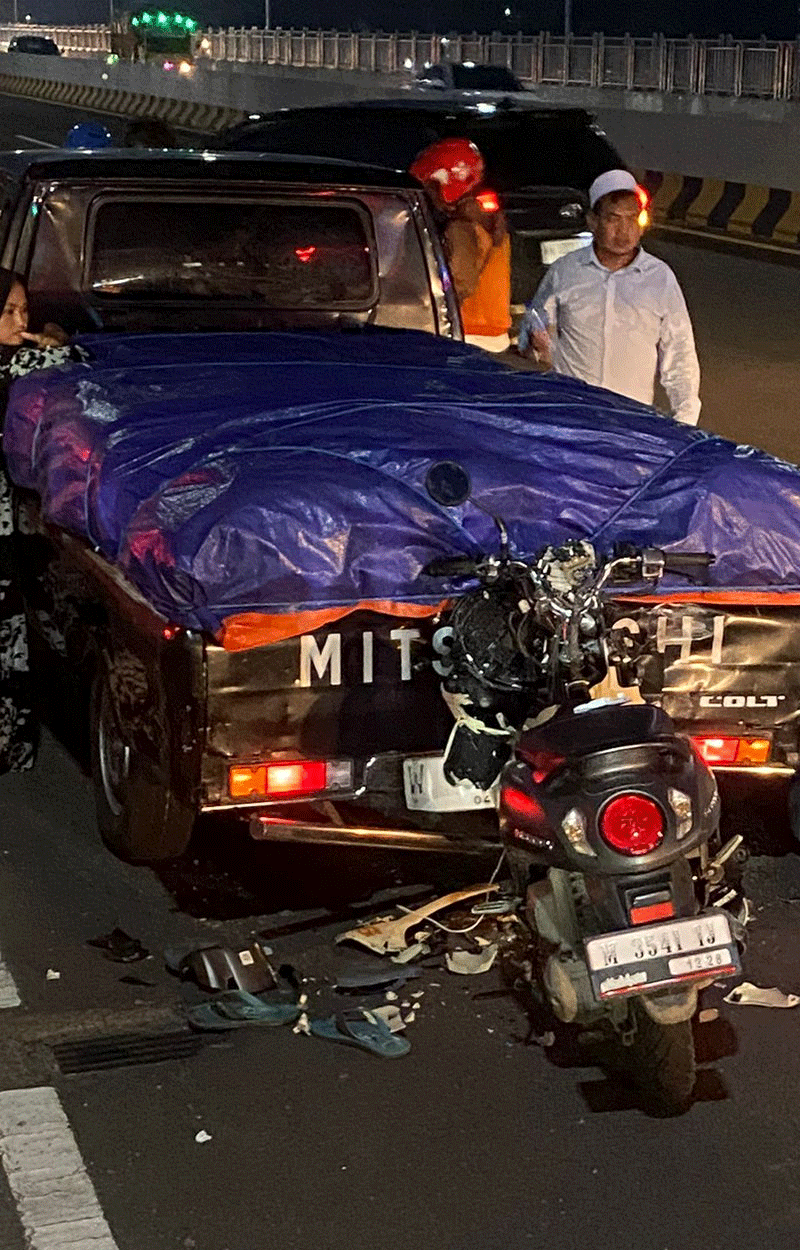Komentar miring masyarakat terhadap putusan hukuman ringan kepada beberapa figur publik yang terjerat kasus pidana sulit dibendung.
Berawal dari kasus mantan Menteri Sosial yang terjerat korupsi bantuan sosial, Jualiari Batubara, yang divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta dan membayar uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar. Dalam sidang tersebut, hakim mengatakan alasan yang meringankan vonis terhadap Jualiari karena Juliari sudah cukup menderita karena mendapatkan “bullying” dari masyarakat.
Baca juga: Terbukti Korupsi Paket Bansos, Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara
Kasus kedua yang baru-baru ini ramai diperbincangkan adalah putusan hakim terhadap Rachel Vennya yang kabur dari karantika sepulang dari Amerika Serikat. Meski divonis bersalah dan mengaku memberi suap, Rachel Vennya tak ditahan. Hakim menjatuhkan vonis 4 bulan penjara, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari Rachel Vennya melakukan suatu tindakan pidana. Keringanan itu diberikan karena hakim juga menilai Rachel juga sopan dan terus terang.
Baca juga: Rachel Vennya Resmi Jadi Tersangka, tapi Tidak Ditahan
Lalu terakhir, yakni kasus Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba. Keduanya dituntut 12 bulan masa rehabilitasi.
Riuh pro dan kontra soal putusan hukum kepada figur publik ini menjadi perbincangan hangat di program Wawasan Radio Suara Surabaya.
“Putusan ini lucu banget, dan lucu kalau dilihatnya karena dibully masyarakat. Harusnya kan dilihat kesalahannya,” kata Laurent.
“Hukum di Indonesia ini kalah dengan yang mayoritas,” kata Suhartono.
“Yang soal narkoba, sikap ini adalah putusan hakim. Secara sistem Undang-undang sudah bagus, tapi pengambil kebijakannya ini yang perlu diketati,” kata Aribowo.
Menaggapi hal ini, Elfina Sahetapy Pengamat Hukum Pidana Universitas Surabaya (Ubaya) angkat bicara. Menurutnya, ada tiga faktor yang membuat mengapa adanya anggapan bahwa hukum di Indonesia cenderung diskriminatif dan tebang pilih.
Pertama, yakni dari sisi materi hukum itu sendiri. Menurutnya, banyak aturan di KUHP yang hanya menyertakan hukuman maksimal, tanpa adanya hukuman minimal penjara.
Ia mencontohkan, kasus penganiyaan di KUHP tertulis maksimal hukuman 5 tahun penjara, tanpa minimal hukuman. Maka jika pelaku penganiyayaan dijerat hukuman selama 1 bulan penjara, maka hal itu sah secara hukum.
“Maksimal 5 tahun, terus kalau dikenai hukuman 1 bulan, hakim tidak salah. Maka tata aturan undang-undang harus dibetulkan. Di dalam rumusan pidana harus ada minimumnya. Minimal 3 tahun misalnya, jadi di bawah 3 tahun tidak bisa,” kata Elfira kepada Radio Suara Surabaya, Jumat (24/12/2021).
Ia menambahkan, “Kita lihat undang-undang kita kebanyakan nggak ada hukuman minimumnya, maka jadinya minimal 1 hari.”
Faktor kedua, yakni adanya faktor pertimbangan hakim yang bisa membuat hukuman menjadi lebih ringan, maupun lebih berat. Sedangkan hakim secara hukum memilikiu wewenang untuk memberikan pertimbangan hukuman.
Menurut Elfira, hal ini bisa menjadi celah jika pertimbangan hakim terlalu subyektif tanpa adanya parameter yang jelas.
“Dari penelitian yang saya baca, di Eropa itu jelas ada indikator dan parameter pertimbangan hakim. Sehingga subyektifitas hakim bisa terukur dan tidak ada diskriminasi,” ungkapnya.
Faktor ketiga, yakni kurangnya transparansi putusan dari pengadilan kepada masyarakat luas.
Elfira menegaskan, memang untuk beberapa sidang digelar secara tertutup, seperti kasus asusila dan kasus hukum terkait anak di bawah umur. Namun, hal itu bukan berarti bahwa putusan tidak dibuka secara umum kepada masyarakat.
“Memang ada beberapa sidang yang digelar tertutup, tapi bukan berarti putusan harus tertutup. Artinya, masyarakat bisa belajar,” paparnya.
Ia menilai, selama ini banyak putusan hukum yang bersifat tertutup sehingga tidak heran jika muncul spekulasi-spekulasi mengenai putusan yang tidak adil oleh hakim.
Menurutnya, itu karena masyarakat juga kurang diberikan akses untuk mengetahui jalannya sebuah kasus pidana.
“Kami yang orang hukum kalau mencari putusan-putusan untuk dianalisis saja cukup kesulitan, tidak punya akses. Apalagi masyarakat. Ini yang membuat putusan hukum harus dibuka agar transparan,” imbuhnya.
Ia juga mengakui adanya disparitas putusan pidana antara pengadilan yang satu dan yang lain, dengan kasus yang sama. Beberapa di antaranya memang bersifat kasuistik. Namun sebagian yang lain kerena pertimbangan hakim.
“Misalnya, pelaku berjanji dan menunjukkan rasa bersalah. Namun di kasus lain, pelaku cuek, menantang. Nah itu jadi pertimbangan hakim yang membuat kasus yang sama, namun hukumannya bisa berbeda. Tapi masih banyak faktor lain yang kadang kita awam memang sulit memahami,” kata Elfira.(tin/ipg)







 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100